Pertama-tama, izinkan saya salin ulang teks aslinya:
KOPER AYAH SAYA (Pidato Nobel Orhan Pamuk)
Dua tahun sebelum kematiannya, ayah saya memberikan kepada saya sebuah koper kecil yang sarat dengan tulisan-tulisan, manuskrip-manuskrip, dan catatan-catatannya. Dengan separuh bercanda dan separuh mencemooh, dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin saya membacanya setelah dia “pergi”, yang artinya setelah dia wafat.
“Coba kau lihat-lihat saja,” katanya, dengan sedikit malu-malu. “Kalau-kalau ada sesuatu di dalamnya yang bisa kau gunakan. Barangkali setelah aku ‘pergi’ kau bisa menyeleksi dan mempublikasikannya.”
Kami berada di ruang studi saya, dikelilingi oleh buku-buku. Ayah saya mencari-cari tempat untuk menaruh koper itu, berjalan mondar-mandir bagaikan seorang yang ingin melepaskan diri dari beban menyakitkan. Pada akhirnya, dia menaruh koper itu dengan khidmat di salah satu sudut ruangan yang tak begitu mencolok. Itu adalah momen memalukan yang tak pernah kami lupakan, namun setelah peristiwa itu lewat, kami kembali kepada peran kami seperti biasa, menghadapi hidup dengan ringan, dengan candaan kami, cemoohan-cemoohan kami yang membuat kami santai. Kami bercengkerama sebagaimana biasa kami lakukan, tentang hal-hal kecil sehari-hari, dan persoalan-persoalan politik Turki yang tak kunjung usai, dan perjalanan-perjalanan bisnis ayah saya yang kebanyakan gagal, tanpa merasa terlalu sedih.
Saya ingat bahwa setelah ayah pergi, saya menghabiskan beberapa hari berjalan mondar-mandir melewati koper itu tanpa sekali pun menyentuhnya. Saya sudah merasa karib dengan koper kulit kecil yang berwarna hitam ini, dan kuncinya, dan sudut-sudut bulatnya. Ayah saya terbiasa membawa-bawa koper itu dalam perjalanan-perjalanan dekat dan terkadang memakainya untuk membawa dokumen buat kerja. Saya ingat bahwa sewaktu saya kecil, dan ayah saya pulang dari suatu perjalanan, saya akan membuka koper kecil ini, menggerayangi benda-benda di dalamnya, seraya menghirup aroma kolonye dan aroma negeri-negeri asing. Koper ini adalah teman yang akrab, pengingat kuat akan masa kecil saya, masa lalu saya, tapi kini saya bahkan tak bisa menyentuhnya. Mengapa? Tak diragukan lagi itu lantaran bobot misterius dari isinya.
Kini saya akan berbicara tentang bobot makna ini. Inilah apa yang seorang ciptakan tatkala dia mengurung diri di kamar, duduk menghadap meja, dan mengundurkan diri dari dunia untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya — dengan kata lain, inilah makna sastra.
Saat saya menyentuh koper ayah saya, saya masih tak kuasa untuk membukanya. Saya tak tahu apa yang ada di dalam catatan-catatan itu. Saya pernah menyaksikan ayah saya menulis banyak hal dalam sejumlah catatan itu. Ini bukanlah kali pertama saya mendengar tentang apa yang ada di dalam koper itu. Ayah saya mempunyai perpustakaan besar; di masa mudanya, pada penghujung tahun 1940-an, dia berkeinginan menjalani kehidupan sebagai penyair di sebuah negara miskin dengan pembaca yang langka. Kakek saya — yakni ayah dari ayah saya — merupakan seorang pengusaha kaya; ayah saya menjalani kehidupan yang nyaman sebagai seorang anak dan seorang remaja, dan dia tak mau bersusah-payah mengalami hidup miskin demi sastra, demi menulis. Ayah saya mencintai kehidupan dengan seluruh keindahannya — ini saya mafhum.
Tentu, hal pertama yang membuat saya tetap berjarak dari isi koper ayah saya adalah ketakutan jangan-jangan ayah saya tak akan menyukai apa yang saya baca. Lantaran ayah saya menyadari hal ini, maka dia melakukan tindak pencegahan dengan berlaku seolah-olah dia tak menganggap isi koper itu sesuatu yang serius. Setelah bekerja sebagai penulis selama dua puluh lima tahun, tindakan ayah saya itu terasa menyakitkan. Tapi saya bahkan tak ingin marah kepada ayah saya dikarenakan tak menganggap sastra sebagai sesuatu yang cukup serius….
Ketakutan saya yang sesungguhnya, hal mustahak yang tak ingin saya ketahui atau temukan, adalah kemungkinan bahwa ayah saya bisa jadi seorang penulis yang baik. Bahkan lebih parah lagi, saya bahkan tak bisa dengan terbuka mengakui hal ini kepada diri saya sendiri. Jikalau itu benar dan karya sastra hebat menyeruak dari koper ayah saya, saya mesti mengakui bahwa di dalam diri ayah saya hadir seseorang yang berbeda sama sekali. Ini kemungkinan yang mengerikan. Lantaran bahkan di usia dewasa saya, saya ingin ayah saya hanya menjadi ayah saya — bukan penulis.
Penulis adalah seorang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba dengan sabar menemukan keberadaan kedua di dalam dirinya, dan menemukan dunia yang membuat dia menjadi siapa dirinya saat ini. Tatkala saya berbicara tentang menulis, apa yang datang pertama-tama ke dalam pikiran saya bukanlah sebuah novel, atau puisi, atau tradisi sastra, melainkan seorang yang mengurung dirinya di dalam kamar, duduk menghadap meja, dan sendirian, melanglang ke dalam batin; di antara bayang-bayang, dia membangun dunia baru dengan kata-kata. Lelaki ini — atau perempuan ini — mungkin menggunakan mesin tik, atau menggunakan jasa komputer, atau menulis dengan pena di atas kertas, seperti yang saya lakukan selama tiga puluh tahun. Saat dia menulis, dia bisa minum teh atau kopi, atau sambil merokok. Dari saat ke saat dia mungkin bangkit dari mejanya untuk menerawang lewat jendela pada anak-anak yang sedang bermain-main di jalanan, dan, jika beruntung, pada pepohonan dan seraut pemandangan, atau dia bisa menatap pada dinding kosong. Dia bisa menulis puisi, atau naskah drama, atau novel, seperti saya. Seluruh perbedaan ini datang setelah tugas mustahak untuk duduk di depan meja dan dengan sabar melanglang ke dalam batin. Menulis adalah mengubah tatapan batin ini ke dalam kata-kata, mempelajari dunia yang darinya dia mengundurkan diri saat dia memandang ke dalam dirinya sendiri, dan melakukannya dengan kesabaran, kekeraskepalaan, dan kegembiraan. Saat saya duduk di meja saya, selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dengan perlahan-lahan menambahkan kata-kata baru ke dalam kertas kosong, saya merasa seolah-olah saya sedang menciptakan dunia baru, seolah-olah saya mengejawantahkan sisi lain dalam diri saya, dalam cara yang sama dengan seseorang yang membangun sebuah jembatan atau kubah, batu demi batu.
Batu-batu yang kami para penulis gunakan adalah kata-kata. Manakala kami menggenggam kata-kata di kedua tangan kami, menelusuri seperti apa tiap-tiap kata ini terhubung dengan kata-kata lainnya, terkadang menatap kepadanya dari kejauhan, terkadang hampir-hampir memeluknya dengan jari jemari kami dan ujung-ujung pena kami, menimbang-nimbangnya, memindah-mindahkannya, seiring tahun demi tahun yang berlalu, dengan sabar dan penuh harap, kami menciptakan dunia-dunia baru. Rahasia penulis bukanlah inspirasi — sebab tak jelas betul dari mana gerangan datangnya — melainkan kekeraskepalaannya, kesabarannya.
Pepatah Turki “menggali sumur dengan sebuah jarum” tampak bagi saya menjadi bingkai dalam pikiran para penulis. Dalam kisah-kisah lawas, saya menyukai kesabaran Ferhat, yang mengali menerobos gunung-gunung demi cintanya — dan saya memahaminya juga. Dalam novel saya My Name is Red, saat saya menulis tentang para pelukis miniatur tua Persia yang melukis kuda yang sama dengan gairah yang sama, mengingat setiap sapuan, selama bertahun-tahun sehingga mereka bisa menciptakan kembali kuda indah itu bahkan dengan mata tertutup, saya tahu saya sedang berbicara tentang profesi menulis, dan kehidupan saya sendiri. Jika seorang penulis mesti mengisahkan ceritanya sendiri — kisahkanlah dengan perlahan-lahan, seolah-olah itu cerita tentang orang lain — jika dia merasa kekuatan cerita bangkit di dalam dirinya, jika dia duduk di depan meja dan dengan tabah menyerahkan dirinya kepada seni ini — kerajinan ini — dia mesti menaruh harap.
Malaikat inspirasi (yang melakukan kunjungan rutin kepada sejumlah orang, dan jarang hinggap kepada yang lainnya) mencintai mereka yang menaruh kepercayaan kepadanya, dan itu adalah ketika si penulis merasa di puncak kesepian, ketika dia merasa paling ragu akan ikhtiar-ikhtiarnya, mimpi-mimpinya, dan nilai dari tulisannya, ketika dia menganggap bahwa kisahnya hanyalah kisahnya — pada saat-saat demikianlah sang malaikat memilih untuk menyingkapkan kepada seorang penulis kisah-kisah, citra-citra, dan mimpi-mimpi yang akan melukis-bayangkan dunia yang ingin dibangunnya. Bila saya merenungkan kembali tentang buku-buku yang terhadapnya saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya, yang paling mencengangkan saya adalah momen-momen manakala saya merasa seakan-akan kalimat-kalimat, mimpi-mimpi, dan halaman-halaman yang telah membawa saya pada puncak kebahagiaan bukanlah berasal dari imajinasi saya sendiri — bahwa kekuatan lain telah menemukan mereka dan dengan murah hati menghamparkannya kepada saya.
Saya takut membuka koper ayah saya dan membaca catatan-catatannya lantaran saya tahu bahwa dia tak akan menoleransi kesulitan-kesulitan yang saya tanggungkan, bahwa bukanlah kesunyian yang dia cintai melainkan kerumunan, salon, lelucon, pergaulan, berkumpul dengan teman-teman. Namun belakangan pikiran-pikiran saya menempuh tikungan yang berbeda. Pikiran-pikiran ini, mimpi-mimpi tentang penampikan dan ketabahan, adalah waham yang saya miliki yang berasal dari kehidupan dan pengalaman saya sendiri sebagai seorang penulis. Ada banyak penulis brilian yang menulis seraya dikelilingi kerumunan dan kehidupan keluarga, dalam pergaulan teman-teman dan percakapan yang menyenangkan. Lagi pula, saat kami muda, ayah saya sudah lelah dengan kehidupan keluarga yang monoton, dan meninggalkan kami untuk menuju ke Paris, di mana — seperti banyak penulis lainnya — dia akan duduk di kamar hotelnya sembari menulis.
Saya juga tahu bahwa sejumlah catatan itu ada di koper tersebut, lantaran selama tahun-tahun sebelum dia membawa koper itu kepada saya, ayah saya akhirnya mulai berbicara ihwal periode dalam kehidupannya itu. Dia berbicara tentang tahun-tahun itu bahkan sewaktu saya masih bocah, namun ayah saya tak menyebut-nyebut tentang kerawanannya, mimpinya menjadi penulis, atau pertanyaan-pertanyaan tentang identitas yang telah merundungnya di kamar hotelnya. Ayah saya alih-alih malah berbicara tentang saat ketika dia berjumpa dengan Sartre di jalanan kota Paris, tentang buku-buku yang telah dia baca dan film-film yang telah dia tonton, segalanya dia katakan dengan kejujuran menggembirakan dari seseorang yang sedang menyampaikan berita-berita yang sangat penting. Tatkala saya menjadi seorang penulis, saya tak akan pernah lupa untuk berterima kasih terhadap kenyataan bahwa saya mempunyai seorang ayah yang terbiasa membincangkan dunia para penulis jauh lebih banyak ketimbang dia membincangkan tentang para pasha atau para pemimpin besar agama. Dengan demikian agaknya saya mesti membaca catatan-catatan ayah saya dengan pikiran semacam itu, dan mengenang betapa berutang budinya saya kepada perpustakaan besarnya.
Saya mesti mengingat bahwa kala dia tinggal bersama kami, ayah saya, seperti saya, sangat menikmati kesendirian bersama buku-buku dan pikiran-pikirannya — dan tak begitu banyak menaruh perhatian pada kualitas literer dari tulisannya.
Namun saat saya menetap dengan begitu cemas pada koper yang diwariskan ayah saya, saya juga merasa bahwa ini justru hal yang tak bisa saya tanggungkan. Ayah saya terkadang akan merentangkan badannya di dipan di hadapan buku-bukunya, meninggalkan buku atau majalah di tangannya, dan mengembara jauh ke dalam sebuah mimpi, melenyapkan diri lama sekali nun di dalam pikiran-pikirannya. Ketika saya memandangi wajahnya, menyeruak sebauh ekspresi yang sangat berbeda dari yang biasanya dia tunjukkan di antara candaan, godaan, dan percekcokan dalam kehidupan keluarga — ketika saya melihat tanda-tanda pertama dari tatapan batin — saya, terutama selama masa kecil dan masa awal remaja saya, akan mengerti dengan rasa gentar, bahwa dia memancarkan ketidakpuasan. Kini, nun bertahun-tahun kemudian, saya menyadari bahwa ketidakpuasan ini adalah raut dasar yang mengubah seseorang menjadi penulis.
Untuk menjadi seorang penulis, kesabaran dan kerja keras belumlah cukup: Pertama-tama kita mesti merasakan dorongan untuk melarikan diri dari kerumunan, pergaulan, rutinitas, kehidupan sehari-hari, dan mengurung diri di dalam kamar. Kita ingin dengan kesabaran dan harapan bisa menciptakan dunia yang mendalam pada tulisan kita. Tapi hasrat untuk mengurung diri di sebuah kamar adalah apa yang mendorong kita ke dalam tindakan. Pendahulu dari penulis independen semacam ini — yang membaca buku-bukunya demi kepuasan hatinya dan yang, dengan hanya mendengarkan suara nuraninya sendiri, berjibaku dengan kata-kata yang lain; yang, dengan memasuki percakapan bersama buku-bukunya, mengembangkan pikiran-pikirannya sendiri, dan dunianya sendiri — tentunya adalah Montaigne, di masa paling awal sastra modern. Montaigne adalah seorang penulis yang terhadapnya ayah saya acap kali kembali, seorang penulis yang dia rekomendasikan kepada saya. Saya melihat diri saya sendiri termasuk ke dalam tradisi dari para penulis yang, di mana pun mereka berada di dunia, di Timur ataupun di Barat, memisahkan diri dari masyarakat dan mengurung diri mereka bersama buku-bukunya di kamar mereka. Titik mula sastra sejati adalah orang-orang yang mengurung dirinya di kamar bersama buku-bukunya.
Saya juga tahu bahwa sejumlah catatan itu ada di koper tersebut, lantaran selama tahun-tahun sebelum dia membawa koper itu kepada saya, ayah saya akhirnya mulai berbicara ihwal periode dalam kehidupannya itu. Dia berbicara tentang tahun-tahun itu bahkan sewaktu saya masih bocah, namun ayah saya tak menyebut-nyebut tentang kerawanannya, mimpinya menjadi penulis, atau pertanyaan-pertanyaan tentang identitas yang telah merundungnya di kamar hotelnya. Ayah saya alih-alih malah berbicara tentang saat ketika dia berjumpa dengan Sartre di jalanan kota Paris, tentang buku-buku yang telah dia baca dan film-film yang telah dia tonton, segalanya dia katakan dengan kejujuran menggembirakan dari seseorang yang sedang menyampaikan berita-berita yang sangat penting. Tatkala saya menjadi seorang penulis, saya tak akan pernah lupa untuk berterima kasih terhadap kenyataan bahwa saya mempunyai seorang ayah yang terbiasa membincangkan dunia para penulis jauh lebih banyak ketimbang dia membincangkan tentang para pasha atau para pemimpin besar agama. Dengan demikian agaknya saya mesti membaca catatan-catatan ayah saya dengan pikiran semacam itu, dan mengenang betapa berutang budinya saya kepada perpustakaan besarnya.
Saya mesti mengingat bahwa kala dia tinggal bersama kami, ayah saya, seperti saya, sangat menikmati kesendirian bersama buku-buku dan pikiran-pikirannya — dan tak begitu banyak menaruh perhatian pada kualitas literer dari tulisannya.
Namun saat saya menetap dengan begitu cemas pada koper yang diwariskan ayah saya, saya juga merasa bahwa ini justru hal yang tak bisa saya tanggungkan. Ayah saya terkadang akan merentangkan badannya di dipan di hadapan buku-bukunya, meninggalkan buku atau majalah di tangannya, dan mengembara jauh ke dalam sebuah mimpi, melenyapkan diri lama sekali nun di dalam pikiran-pikirannya. Ketika saya memandangi wajahnya, menyeruak sebauh ekspresi yang sangat berbeda dari yang biasanya dia tunjukkan di antara candaan, godaan, dan percekcokan dalam kehidupan keluarga — ketika saya melihat tanda-tanda pertama dari tatapan batin — saya, terutama selama masa kecil dan masa awal remaja saya, akan mengerti dengan rasa gentar, bahwa dia memancarkan ketidakpuasan. Kini, nun bertahun-tahun kemudian, saya menyadari bahwa ketidakpuasan ini adalah raut dasar yang mengubah seseorang menjadi penulis.
Untuk menjadi seorang penulis, kesabaran dan kerja keras belumlah cukup: Pertama-tama kita mesti merasakan dorongan untuk melarikan diri dari kerumunan, pergaulan, rutinitas, kehidupan sehari-hari, dan mengurung diri di dalam kamar. Kita ingin dengan kesabaran dan harapan bisa menciptakan dunia yang mendalam pada tulisan kita. Tapi hasrat untuk mengurung diri di sebuah kamar adalah apa yang mendorong kita ke dalam tindakan. Pendahulu dari penulis independen semacam ini — yang membaca buku-bukunya demi kepuasan hatinya dan yang, dengan hanya mendengarkan suara nuraninya sendiri, berjibaku dengan kata-kata yang lain; yang, dengan memasuki percakapan bersama buku-bukunya, mengembangkan pikiran-pikirannya sendiri, dan dunianya sendiri — tentunya adalah Montaigne, di masa paling awal sastra modern. Montaigne adalah seorang penulis yang terhadapnya ayah saya acap kali kembali, seorang penulis yang dia rekomendasikan kepada saya. Saya melihat diri saya sendiri termasuk ke dalam tradisi dari para penulis yang, di mana pun mereka berada di dunia, di Timur ataupun di Barat, memisahkan diri dari masyarakat dan mengurung diri mereka bersama buku-bukunya di kamar mereka. Titik mula sastra sejati adalah orang-orang yang mengurung dirinya di kamar bersama buku-bukunya.
Tapi sekali kita mengurung diri, kita akan segera menemukan bahwa kita tak sesendiri sebagaimana yang kita bayangkan. Kita akan ditemani oleh kata-kata dari mereka yang datang sebelum kita, oleh kisah-kisah orang lain, buku-buku orang lain, kata-kata orang lain, sesuatu yang kita namakan tradisi. Saya percaya bahwa sastra merupakan timbunan yang paling berharga yang telah dihimpun umat manusia dalam pencariannya untuk memahami diri mereka sendiri. Masyarakat-masyarakat, suku-suku, dan orang-orang tumbuh lebih cerdas, lebih kaya, dan lebih maju saat mereka menaruh perhatian kepada kata-kata sulit dari para penulis mereka, dan, sebagaimana yang kita ketahui, pembakaran buku-buku dan penistaan terhadap para penulis merupakan isyarat bahwa zaman yang gelap dan sia-sia sedang merundung kita. Namun sastra tak pernah hanya menjadi perhatian nasional. Penulis yang mengurung dirinya di sebuah kamar dan pertama-tama melakukan petualangan ke dalam batinnya sendiri selama bertahun-tahun akan menemukan aturan abadi sastra: Dia mesti memiliki kemampuan untuk mengisahkan cerita-ceritanya sendiri seolah-olah itu adalah cerita orang lain, dan mengisahkan cerita-cerita orang lain seolah-olah itu cerita-ceritanya sendiri, lantaran inilah sastra sejati itu. Tapi pertama-tama kita mesti menjelajahi cerita-cerita dan buku-buku orang lain.
Ayah saya mempunyai perpustakaan yang bagus — seluruh koleksinya berjumlah seribu lima ratus jilid, jumlah yang lebih cukup buat seorang penulis. Pada usia dua puluh dua tahun, saya mungkin tak membaca semua buku tersebut, namun saya akrab dengan tiap buku itu — saya tahu yang mana buku-buku yang penting, yang mana yang ringan tapi enak dibaca, yang mana yang klasik, yang mana yang mustahak buat pendidikan, yang mana yang mudah dilupakan tapi menghibur tentang sejarah lokal, dan buku-buku dari para penulis Prancis yang dinilai sangat luhur oleh ayah saya. Terkadang saya akan memandangi perpustakaan itu dari kejauhan dan membayangkan bahwa suatu hari, di rumah yang berbeda, saya akan membangun perpustakaan saya sendiri, sebuah perpustakaan yang bahkan lebih baik lagi dari perpustakaan ayah saya — membangun dunia saya sendiri.
Manakala saya memandangi perpustakaan ayah saya dari kejauhan, tampak bagi saya ia penaka lukisan kecil dari dunia nyata. Namun ini adalah sebuah dunia yang dilihat dari sudut kami sendiri, dari Istanbul. Perpustakaan itu adalah bukti dari ini. Ayah saya telah membangun perpustakaannya dari perjalanan-perjalanannya ke luar negeri, kebanyakan dengan buku-buku dari Paris dan Amerika, namun juga dengan buku-buku yang dibeli dari toko-toko yang menjual buku-buku asing pada 1940-an dan 1950-an dan toko buku-toko buku Istanbul yang lama maupun baru, yang juga saya tahu.
Manakala saya memandangi perpustakaan ayah saya dari kejauhan, tampak bagi saya ia penaka lukisan kecil dari dunia nyata. Namun ini adalah sebuah dunia yang dilihat dari sudut kami sendiri, dari Istanbul. Perpustakaan itu adalah bukti dari ini. Ayah saya telah membangun perpustakaannya dari perjalanan-perjalanannya ke luar negeri, kebanyakan dengan buku-buku dari Paris dan Amerika, namun juga dengan buku-buku yang dibeli dari toko-toko yang menjual buku-buku asing pada 1940-an dan 1950-an dan toko buku-toko buku Istanbul yang lama maupun baru, yang juga saya tahu.
Dunia saya adalah perbauran antara yang lokal — yang nasional — dan Barat. Pada 1970-an, saya juga mulai, dengan ambisius, membangun perpustakaan saya sendiri. Saya belum memutuskan secara pasti untuk menjadi seorang penulis — seperti yang saya ceritakan dalam Istanbul, tapi saya sudah merasa bahwa saya bagaimanapun tak akan menjadi pelukis, walaupun saya belum tahu pasti jalan apa yang akan saya tempuh dalam kehidupan saya. Dalam diri saya ada rasa penasaran yang mengelisahkan, harapan yang menggerakkan hasrat untuk membaca dan belajar, namun pada saat yang sama saya merasa bahwa dalam beberapa cara kehidupan saya kekurangan, bahwa saya tak akan bisa hidup seperti orang-orang lain. Saat saya memandangi perpustakaan ayah saya, saya tak bisa berpikir bahwa hidup saya jauh dari pusat segalanya, di sebuah pinggiran, impresi yang dirasakan juga oleh kita semua yang hidup di Istanbul pada masa itu. Ada alasan lain buat kecemasan saya, dan ketakutan saya menjalani hidup kekurangan, lantaran saya juga tahu dengan baik bahwa saya hidup di sebuah negara yang menunjukkan sedikit ketetarikan kepada para seniman-senimannya, para pelukis dan penulisnya, dan tak memberi mereka harapan. Pada tahun tujuh puluhan, saat saya menerima uang yang diberikan ayah saya dan dengan rakus membeli buku-buku lawas yang berdebu dan sudah dimakan rayap dari toko buku- toko buku bekas ini — dan oleh kekusutan mengenaskan dari pada penjual buku miskin dan rudin yang membentangkan barang-barang dagangan mereka di pinggir-pinggir jalan, di pekarangan-pekarangan masjid, dan di relung-relung dinding yang runtuh — seterpengaruh saya oleh buku-buku mereka.
Demikianlah pula dengan tempat saya di dunia — dalam kehidupan, seperti halnya dalam sastra, perasaan dasar saya adalah bahwa saya tidaklah berada di pusat. Di pusat dunia ada kehidupan yang lebih kaya dan lebih menyenangkan ketimbang kehidupan kami, dan bersamaan dengan seluruh Istanbul, seluruh Turki, saya berada di luarnya. Kini saya kira saya berbagi perasaan ini dengan banyak sekali orang di dunia. Dalam cara yang sama, ada sebuah sastra dunia, dan juga pusatnya, yang sangat jauh dari saya. Sesungguhnya apa yang ada dalam benak saya adalah Barat, bukanlah dunia dan sastra, dan kami orang-orang Turki berada di luarnya. Perpustakaan ayah saya adalah bukti tentang hal ini. Di ujung yang satu, ada buku-buku Istanbul — sastra kami, dunia lokal kami, dalam seluruh rinciannya yang tercinta — dan di ujung yang lain adalah buku-buku dari dunia Barat yang lain itu, yang terhadapnya dunia kami tak memiliki kesamaan apapun, yang terhadapnya kurangnya kesamaan itu memberi kami rasa sakit dan harapan. Laku menulis, laku membaca, bagaikan meninggalkan satu dunia untuk menemukan penghiburan dalam kelainan dunia lain, dunia yang ajaib dan menakjubkan.
Saya merasa bahwa ayah saya membaca novel-novel untuk melarikan diri dari kehidupannya dan terbang ke Barat — sebagaimana yang saya lakukan di kemudian hari. Bukan hanya dengan membaca bahwa kami meninggalkan kehidupan Istanbul kemi untuk melawat ke Barat — melainkan juga dengan menulis. Demi memenuhi catatan-catatannya, ayah saya telah pergi ke Paris, mengurung diri di kamar hotelnya, dan lantas membawa tulisan-tulisannya kembali ke Turki. Saat saya memandangi koper ayah saya, tampak bagi saya inilah apa yang merebakkan kegelisahan dalam diri saya. Setelah bekerja di sebuah kamar selama dua puluh lima tahun bertahan sebagai penulis di Turki, sungguh menyesakkan dada mengetahui bahwa ayah saya menyembunyikan pikiran-pikiran mendalamnya di dalam koper ini, bertindak seolah-olah menulis ialah pekerjaan yang mesti dilakukan secara rahasia, jauh dari mata masyarakat, negara, orang-orang lain. Barangkali inilah alasan utama mengapa saya marah kepada ayah saya lantaran tak menganggap sastra seserius seperti halnya saya.
Saya merasa bahwa ayah saya membaca novel-novel untuk melarikan diri dari kehidupannya dan terbang ke Barat — sebagaimana yang saya lakukan di kemudian hari. Bukan hanya dengan membaca bahwa kami meninggalkan kehidupan Istanbul kemi untuk melawat ke Barat — melainkan juga dengan menulis. Demi memenuhi catatan-catatannya, ayah saya telah pergi ke Paris, mengurung diri di kamar hotelnya, dan lantas membawa tulisan-tulisannya kembali ke Turki. Saat saya memandangi koper ayah saya, tampak bagi saya inilah apa yang merebakkan kegelisahan dalam diri saya. Setelah bekerja di sebuah kamar selama dua puluh lima tahun bertahan sebagai penulis di Turki, sungguh menyesakkan dada mengetahui bahwa ayah saya menyembunyikan pikiran-pikiran mendalamnya di dalam koper ini, bertindak seolah-olah menulis ialah pekerjaan yang mesti dilakukan secara rahasia, jauh dari mata masyarakat, negara, orang-orang lain. Barangkali inilah alasan utama mengapa saya marah kepada ayah saya lantaran tak menganggap sastra seserius seperti halnya saya.
Sebelumnya saya marah kepada ayah saya lantaran dia tak menjalani hidup sebagaimana saya, lantaran dia tak pernah berkelahi dengan kehidupannya, dan lantaran dia telah menghabiskan hidupnya dengan bahagia tertawa-tawa bersama teman-temannya dan orang-orang tercintanya. Namun bagian dari diri saya menyadari bahwa saya juga bisa mengatakan bahwa saya lebih tepatnya merasa cemburu ketimbang marah. Kata cemburu itulah yang lebih tepat dan ini mebuat saya resah. Itu akan terasa manakala saya bertanya kepada diri sendiri dengan nada suara yang mencemooh dan marah:
Apakah kebahagiaan itu?
Adakah kebahagiaan itu menjalani kehidupan mendalam di ruangan kamar yang sunyi-senyap? Atau, adakah kebahagiaan itu menjalani kehidupan yang nyaman dalam masyarakat, memercayai segala hal yang sama dengan yang mereka percayai, atau berlagak seakan-akan Anda memercayainya?
Adakah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan, apabila menjalani kehidupan dengan menulis secara rahasia, seraya pada saat yang sama tampak harmoni dengan segala sesuatu di sekitar Anda?
Namun, semua ini hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang menggelikan. Entah dari mana saya mendapat gagasan bahwa ukuran dari kehidupan yang baik adalah kebahagiaan? Orang-orang, koran-koran, setiap orang bertindak seakan-akan ukuran yang paling penting dari kehidupan adalah kebahagiaan. Bagaimana gerangan kalau sebaliknya yang benar? Bagaimanapun, ayah saya acap melarikan diri dari keluarganya — seberapa jauh saya mengetahuinya, dan seberapa jauh saya bisa memahami kegelisahannya?
Apakah kebahagiaan itu?
Adakah kebahagiaan itu menjalani kehidupan mendalam di ruangan kamar yang sunyi-senyap? Atau, adakah kebahagiaan itu menjalani kehidupan yang nyaman dalam masyarakat, memercayai segala hal yang sama dengan yang mereka percayai, atau berlagak seakan-akan Anda memercayainya?
Adakah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan, apabila menjalani kehidupan dengan menulis secara rahasia, seraya pada saat yang sama tampak harmoni dengan segala sesuatu di sekitar Anda?
Namun, semua ini hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang menggelikan. Entah dari mana saya mendapat gagasan bahwa ukuran dari kehidupan yang baik adalah kebahagiaan? Orang-orang, koran-koran, setiap orang bertindak seakan-akan ukuran yang paling penting dari kehidupan adalah kebahagiaan. Bagaimana gerangan kalau sebaliknya yang benar? Bagaimanapun, ayah saya acap melarikan diri dari keluarganya — seberapa jauh saya mengetahuinya, dan seberapa jauh saya bisa memahami kegelisahannya?
Jadi, inilah yang menggerakkan saya ketika kali pertama saya membuka koper ayah saya. Apakah ayah saya punya rahasia, ketidakbahagiaan dalam kehidupannya yang tentangnya saya tak mengetahui sama sekali, sesuatu yang hanya bisa dia tanggungkan dengan mencurahkannya ke dalam tulisannya? Segera setelah saya membuka koper tersebut, saya mengingat bau perjalanan yang menguar darinya, mengenali sejumlah catatan, dan menyadari bahwa ayah saya pernah menunjukkan catatan-catatan tersebut kepada saya beberapa tahun sebelumnya, namun dalam waktu yang hanya sebentar saja. Kebanyakan dari catatan-catatan yang kini ada di genggaman saya ditulis ayah saya saat dia meninggalkan kami dan melawat ke Paris sebagai seorang lelaki muda.
Sementara itu, saya seperti banyak penulis lain yang saya kagumi — berharap mengetahui apa yang ayah saya tulis, dan apa yang ayah saya pikirkan, saat dia seusia dengan saya sekarang. Tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa saya tak akan menemukan apapun yang semacam itu di sini. Apa yang menyebabkan saya paling gelisah adalah ketika, di sana-sini dalam catatan ayah saya, saya menjumpai suara penulis. Ini bukanlah suara ayah saya, demikian saya katakan kepada diri sendiri; suara itu tidaklah autentik, atau setidaknya suara itu bukanlah milik lelaki yang saya kenal sebagai ayah saya. Di bawah ketakutan saya bahwa ayah saya mungkin bukanlah ayah saya tatkala dia menulis, terdapat ketakutan yang lebih mendalam: ketakutan bahwa jauh di kedalaman batin saya, saya tidaklah autentik, bahwa saya tak akan menemukan apapun yang baik dalam tulisan ayah saya. Ketakutan saya bertambah besar saat saya menemukan bahwa ayah saya sangat terpengaruh oleh penulis-penulis lain dan menggelincirkan saya ke dalam keputusasaan yang telah merundung sama demikian kuatnya saat saya muda, melemparkan hidup saya, diri saya, hasrat saya untuk menulis, dan karya saya ke dalam kebimbangan. Selama sepuluh tahun saya menjadi penulis, saya merasakan kecemasan-kecemasan ini dengan lebih mendalam, dan bahkan tatkala saya berjibaku mengusirnya, saya terkadang takut bahwa suatu hari, saya mesti mengakui bahwa saya kalah — sebagaimana yang saya lakukan terhadap lukisan — dan, tunduk pada kegelisahan, dan juga menyerah untuk menulis novel.
Sementara itu, saya seperti banyak penulis lain yang saya kagumi — berharap mengetahui apa yang ayah saya tulis, dan apa yang ayah saya pikirkan, saat dia seusia dengan saya sekarang. Tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa saya tak akan menemukan apapun yang semacam itu di sini. Apa yang menyebabkan saya paling gelisah adalah ketika, di sana-sini dalam catatan ayah saya, saya menjumpai suara penulis. Ini bukanlah suara ayah saya, demikian saya katakan kepada diri sendiri; suara itu tidaklah autentik, atau setidaknya suara itu bukanlah milik lelaki yang saya kenal sebagai ayah saya. Di bawah ketakutan saya bahwa ayah saya mungkin bukanlah ayah saya tatkala dia menulis, terdapat ketakutan yang lebih mendalam: ketakutan bahwa jauh di kedalaman batin saya, saya tidaklah autentik, bahwa saya tak akan menemukan apapun yang baik dalam tulisan ayah saya. Ketakutan saya bertambah besar saat saya menemukan bahwa ayah saya sangat terpengaruh oleh penulis-penulis lain dan menggelincirkan saya ke dalam keputusasaan yang telah merundung sama demikian kuatnya saat saya muda, melemparkan hidup saya, diri saya, hasrat saya untuk menulis, dan karya saya ke dalam kebimbangan. Selama sepuluh tahun saya menjadi penulis, saya merasakan kecemasan-kecemasan ini dengan lebih mendalam, dan bahkan tatkala saya berjibaku mengusirnya, saya terkadang takut bahwa suatu hari, saya mesti mengakui bahwa saya kalah — sebagaimana yang saya lakukan terhadap lukisan — dan, tunduk pada kegelisahan, dan juga menyerah untuk menulis novel.
Saya sudah mengutarakan dua perasaan utama yang bangkit saat saya menutup koper ayah saya dan menaruhnya kembali: perasaan ditinggalkan di sebuah daerah pinggiran, dan ketakutan bahwa saya kekurangan autentisitas. Ini tentunya bukan kali pertama saya merasakan kilasan perasaan-perasaan itu. Selama bertahun-tahun, saya — dalam bacaan dan tulisan saya — telah mempelajari, menemukan, memperdalam emosi-emosi tersebut, dalam berbagai wujud, konsekuensi-konsekuensi yang tak terduga, akhir yang menegangkan, pemicu-pemicu, dan berbagai jenisnya. Tentunya jiwa saya telah dikejutkan oleh pelbagai kebingungan, sensitivitas, dan kesakitan mengambang yang diteriakan buku-buku dan kehidupan ke dalam diri saya, sering kali sebagai seorang anak muda. Tetapi hanya dengan menulis buku-bukulah saya menjadi paham secara penuh seluruh problem autentisitas (seperti dalam My Name is Red dan The Black Book) dan problem kehidupan pinggiran (seperti dalam Snow dan Istanbul). Bagi saya, menjadi penulis adalah mengenali luka-luka rahasia yang kita bawa dalam diri kita, dan dengan sabar mengeksplorasinya, mengiluminasinya, menjadikan luka dan kesakitan itu milik kita sendiri, dan untuk membuat mereka menjadi bagian sadar dari jiwa dan tulisan kita.
Seorang penulis berbicara tentang segala sesuatu untuk semua orang tahu namun tak tahu bahwa mereka tahu. Untuk mengeksplorasi pengetahuan ini, dan untuk menyaksikannya tumbuh, adalah hal yang menyenangkan; si pembaca sedang mengunjungi sebuah dunia yang akrab sekaligus menakjubkan. Tatkala seorang penulis mengurung dirinya di sebuah kamar selama bertahun-tahun untuk mengasah keterampilannya — untuk menciptakan sebuah dunia — jikalau dia menggunakan luka-luka rahasianya sebagai titik tolak, maka dia, entah menyadarinya atau tidak, sesungguhnya menaruh kepercayaan yang besar terhadap manusia. Kepercayaan saya datang dari kepercayaan bahwa seluruh umat manusia mirip satu sama lain, bahwa orang-orang lain juga mempunyai luka seperti luka saya — dan oleh karena itu mereka akan mengerti. Seluruh sastra sejati terbit dari keyakinan yang kekanakan dan penuh harap ini, yakni bahwa seluruh manusia mirip satu sama lain. Saat sang penulis mengurung dirinya di sebuah kamar selama bertahun-tahun, dengan isyarat ini dia mengilaskan kemanusiaan tunggal, sebuah dunia tanpa pusat.
Tapi seperti bisa dilihat dari koper ayah saya dan warna-warna pudar dari kehidupan kami di Istanbul, dunia betul-betul mempunyai pusat, dan pusat itu jauh dari kami. Dalam buku-buku saya, saya telah dalam sejumlah detail bagaimana fakta mendasar ini membangkitkan perasaan Chekovian akan pinggiran, dan bagaimana, dengan jalan lain, hal itu menggiring pada pertanyaan saya tentang autentitas saya. Dari pengalaman, saya tahu bahwa mayoritas manusia di bumi ini hidup dengan perasaan-perasaan yang sama, dan bahwa banyak yang menderita dari rasa ketakmemadaian, kurangnya keamanan, dan rasa akan penistaan yang bahkan lebih dalam lagi ketimbang saya. Ya, dilema terbesar yang dihadapi umat manusia adalah ketiadaan tanah, ketiadaan rumah, serta kelaparan, tapi kini televisi dan koran-koran mengabarkan kepada kita tentang problem-problem mendasar ini, lebih cepat dan lebih sederhana ketimbang yang bisa dilakukan sastra. Yang paling diperlukan untuk dikisahkan dan diselidiki oleh sastra kini adalah ketakutan dasar manusia: ketakutan ditinggal di luar, dan ketakutan untuk tak dianggap apapun, dan perasaan tak berharga yang datang bersamaan dengan ketakutan-ketakutan semacam itu; penghinaan kolektif, kerawanan, pelalaian, keluhan, sensitivitas, penistaan imajiner, kebanggaan nasionalis, dan inflasi yang menyertainya..
Kapan pun saya dihadapkan kepada sentimen-sentimen serupa itu, dan kepada bahasa irasional penuh bual yang dengannya hal itu biasanya diekspresikan, saya menyadari bahwa mereka menyentuh kegelapan dalam batin saya. Acap kali kita menyaksikan orang-orang, masyarakat, dan bangsa-bangsa di luar Barat — dan dengan mudah saya bisa mengidentifikasikan diri dengan mereka — tunduk pada ketakutan yang terkadang menggiring mereka kepada kebodohan. Semua dikarenakan ketakutan mereka akan penistaan dan sensitivitas mereka. Saya juga tahu bahwa di Barat — sebuah dunia yang dengannya saya bisa mengidentifikasikan diri dengan mereka — bangsa-bangsa dan masyarakat-masyarakatnya merasakan kebanggaan terhadapa kejayaan mereka dan itu dikarenakan mereka membawakan kepada kita renaisans, pencerahan, dan modernisme, sehingga dari waktu ke waktu terjerumus pada kepuasan diri yang nyaris sama bodohnya.
Kapan pun saya dihadapkan kepada sentimen-sentimen serupa itu, dan kepada bahasa irasional penuh bual yang dengannya hal itu biasanya diekspresikan, saya menyadari bahwa mereka menyentuh kegelapan dalam batin saya. Acap kali kita menyaksikan orang-orang, masyarakat, dan bangsa-bangsa di luar Barat — dan dengan mudah saya bisa mengidentifikasikan diri dengan mereka — tunduk pada ketakutan yang terkadang menggiring mereka kepada kebodohan. Semua dikarenakan ketakutan mereka akan penistaan dan sensitivitas mereka. Saya juga tahu bahwa di Barat — sebuah dunia yang dengannya saya bisa mengidentifikasikan diri dengan mereka — bangsa-bangsa dan masyarakat-masyarakatnya merasakan kebanggaan terhadapa kejayaan mereka dan itu dikarenakan mereka membawakan kepada kita renaisans, pencerahan, dan modernisme, sehingga dari waktu ke waktu terjerumus pada kepuasan diri yang nyaris sama bodohnya.
Jikalau demikian, maka ayah saya bukanlah satu-satunya, bahwa kita semua memberi arti terlampau penting terhadap gagasan tentang sebuah dunia dengan pusat. Padahal, hal yang menyeret kita untuk mengurung diri menulis di kamar-kamar kita selama bertahun-tahun adalah segaris kepercayaan yang bertentangan dengan itu: kepercayaan bahwa suatu hari tulisan-tulisan kita akan dibaca dan dipahami, lantaran manusia di seluruh dunia bermiripan satu sama lain. Namun ini, seperti yang saya ketahui dari tulisan saya dan ayah saya, adalah optimisme yang bermasalah, dihantui oleh kemarahan karena dibuang ke pinggiran, atau ditinggalkan di luar. Cinta dan benci yang dirasakan Dostoyevsky terhadap Barat sepanjang hidupnya — saya merasakannya juga, dalam banyak kesempatan. Tapi bila saya meraih kebenaran esensial, bila saya punya dalih untuk optimisme, itu dikarenakan saya telah berkelana dengan penulis besar ini ke dalam hubungan cinta-benci dengan Barat, untuk menyaksikan dunia lain yang telah dia bangun di sisi lain.
Seluruh penulis yang telah mempersembahkan kehidupan mereka pada tugas ini akan tahu kenyataan ini: Apapun tujuan asli kita, dunia yang kita ciptakan setelah bertahun-tahun menulis dengan sepenuh harap akan, pada akhirnya, bergerak ke tempat-tempat lain yang berbeda. Dunia itu akan membawa kita jauh dari meja tempat kita bekerja dengan kesedihan atau kemarahan, membawa kita ke sisi lain dari kesedihan dan kemarahan itu, menuju dunia lain. Adakah ayah saya tak bisa mencapai dunia semacam itu? Ibarat lahan yang perlahan-lahan mulai beroleh bentuknya, pelan-pelan muncul dari kabut dalam segala warna-warninya bagai pulau selepas pelayaran laut yang panjang, dunia lain ini memesona kita. Kita sama terperdayanya dengan para penjelajah Barat yang berlayar dari selatan untuk menyaksikan Istanbul muncul dari kabut. Di ujung perjalanan, yang dimulai dengan harapan dan penasaran, terbentang di sana, di hadapan mereka, kota masjid-masjid dan menara, rampaian rumah-rumah, jalanan, bukit-bukit, jembatan-jembatan, dan lembah-lembah, dan seluruh dunia. Menyaksikan itu, kita berharap memasuki dunia ini dan melenyapkan diri di dalamnya, selaiknya dalam sebuah buku. Setelah duduk di meja lantaran kita merasa diri udik, terasing, di pinggiran, marah, atau merasakan melankolia yang mendalam, kita lantas menemukan seluruh dunia di sebalik sentimen-sentimen ini.
Apa yang saya rasakan sekarang adalah bertentangan dari apa yang saya rasakan sebagai seorang anak dan seoran pemuda: bagi saya pusat dunia itu adalah Istanbul. Ini bukan hanya karena saya telah bermukim di sana dalam seluruh hidup saya, tapi lantaran selama tiga puluh tahun terakhir saya telah mengisahkan jalan-jalannya, jembatan-jembatannya, orang-orangnya, anjing-anjingnya, rumah-rumahnya, masjid-masjidnya, air mancur-air mancurnya, pahlawan-pahlawannya yang aneh, tokoh-tokohnya, karakter-karakter terkenalnya, titik-titik gelapnya, siang-siangnya dan malam-malamnya, menjadikan mereka bagian dari saya, seraya memeluk mereka semua. Datang masa ketika dunia saya telah saya buat dengan tangan-tangan saya ini, dunia yang hanya ada di kepala saya ini, tampak lebih nyata bagi saya ketimbang kota sesungguhnya yang saya tinggali. Itu terjadi tatkala seluruh orang dan jalan-jalan ini, objek-objek dan bangunan-bangunan tampak mulai bercengkerama satu sama lain, dan mulai berinteraksi dalam cara yang tak saya duga sebelumya, seakan-akan mereka bukan hanya hidup di dalam imajinasi saya atau buku-buku saya, melainkan hidup bagi mereka sendiri. Dunia yang saya ciptakan ini penaka seorang lelaki yang sedang menggali sumur dengan sebuah jarum, tampak lebih sejati ketimbang seluruh hal lainnya.
Ayah saya juga mungkin telah menemukan kebahagiaan semacam ini selama tahun-tahun yang dia habiskan untuk menulis, demikian yang ada dalam pikiran saya saat saya memandangi koper ayah saya: Saya tak seharusnya menaruh purbasangka kepadanya. Bagaimanapun, saya sangat berterimakasih kepadanya: dia tak pernah menjadi seorang ayah yang memerintah, melarang, menguasai, menghukum, selaiknya ayah biasa, melainkan ayah yang selalu membuat saya bebas, selalu menunjukkan kepada saya rasa hormat yang mendalam. Acap saya berpikir bahwa jika saya bisa menulis dari imajinasi saya, dari saat ke saat, itu lantaran — tak seperti banyak teman saya dari masa kanak dan remaja — saya tak takut kepada ayah saya, dan terkadang saya percaya bahwa saya bisa menjadi penulis karena ayah saya juga ingin menjadi penulis di masa mudanya. Saya mesti membacanya dengan toleran — menelisik demi memahami apa yang sudah dia tulis di kamar-kamar hotel itu.
Dengan harapan seperti itu dalam benak saya, maka saya beranjak menuju koper itu, yang masih berada di tempat ayah saya menaruhnya dulu; dengan mengerahkan seluruh tekad saya, saya membaca dengan saksama sejumlah manuskrip dan catatan. Pokok apa yang ditulis oleh ayah saya? Saya terkenang secercah pemandangan dari jendela hotel-hotel Paris, sejumput puisi, paradoks, analisis… saat saya menulis saya merasa seperti seseorang yang baru saja mengalami kecelakaan lalulintas dan berusaha sekuat tenaga mengingat-ingat bagaimana hal itu terjadi, sementara pada saat yang sama merasa ngeri tentang kemungkinan mengingat terlalu banyak. Tatkala saya kecil, dan ayah serta ibu saya berada di ambang pertengkaran — saat masing-masing dari mereka berdiam diri — ayah saya biasanya akan menyembunyikan radio untuk mengubah suasana hati, dan alunan musik akan membantu kita melupakan segalanya lebih cepat.
Perkenankan saya mengubah suasana hati dengan beberapa kata manis yang saya harap akan terdengar bagaikan musik. Seperti Anda sekalian ketahui, pertanyaan yang kerap diajukan oleh kita para penulis, pertanyaan favorit, adalah: Mengapa Anda menulis? Mengapa saya menulis? Saya menulis karena saya punya dorongan batin untuk menulis! Saya menulis karena saya tak bisa melakukan perkerjaan normal seperti orang-orang lain. Saya menulis karena saya ingin membaca buku-buku seperti buku-buku yang saya tulis. Saya menulis karena saya marah kepada Anda semua, marah kepada siapapun. Saya menulis karena saya suka duduk di sebuah kamar sepanjang hari untuk menulis. Saya menulis karena saya ingin orang-orang lain, kita semua, seluruh dunia, mengetahui kehidupan seperti apa yang kami jalani, dan terus kami jalani, di Istanbul, di Turki. Saya menulis karena saya menyukai bau kertas, pena, dan tinta. Saya menulis karena saya percaya pada sastra, pada seni novel, lebih dari kepercayaan saya pada yang lainnya. Saya menulis karena ia adalah kebiasaan, gairah. Saya menulis karena saya takut dilupakan. Saya menulis karena menyukai kejayaan dan kesenangan yang diwedarkan tulisan. Saya menulis untuk menjadi sendirian.
Barangkali saya menulis karena saya berharap untuk mengerti mengapa saya marah, sangat marah, kepada Anda sekalian, begitu marah, sangat marah, kepada semua orang. Saya menulis karena saya ingin dibaca. Saya menulis karena sekali saya menulis sebuah novel, atau seraut esai, selembar halaman, saya selalu ingin menyelesaikannya. Saya menulis karena semua orang berharap saya menulis. Saya menulis karena saya mempunyai kepercayaan kekanakan kepada keabadian perpustakaan, dan dalam cara buku-buku saya tersusun di atas rak buku. Saya menulis karena sungguh menggembirakan mengubah seluruh keindahan dan kekayaan hidup ke dalam kata-kata-kata. Saya menulis bukan untuk menceritakan sebuah kisah, melainkan menyusunnya. Saya menulis karena saya ingin melarikan diri dari nubuat bahwa ada sebuah tempat yang mesti saya kunjungi — bagai dalam mimpi — tapi saya tak bisa ke sana. Saya menulis karena saya tak pernah bisa bahagia. Saya menulis untuk bahagia.
Barangkali saya menulis karena saya berharap untuk mengerti mengapa saya marah, sangat marah, kepada Anda sekalian, begitu marah, sangat marah, kepada semua orang. Saya menulis karena saya ingin dibaca. Saya menulis karena sekali saya menulis sebuah novel, atau seraut esai, selembar halaman, saya selalu ingin menyelesaikannya. Saya menulis karena semua orang berharap saya menulis. Saya menulis karena saya mempunyai kepercayaan kekanakan kepada keabadian perpustakaan, dan dalam cara buku-buku saya tersusun di atas rak buku. Saya menulis karena sungguh menggembirakan mengubah seluruh keindahan dan kekayaan hidup ke dalam kata-kata-kata. Saya menulis bukan untuk menceritakan sebuah kisah, melainkan menyusunnya. Saya menulis karena saya ingin melarikan diri dari nubuat bahwa ada sebuah tempat yang mesti saya kunjungi — bagai dalam mimpi — tapi saya tak bisa ke sana. Saya menulis karena saya tak pernah bisa bahagia. Saya menulis untuk bahagia.
Seminggu setelah ayah saya datang ke kantor saya dan memberikan kopernya, dia datang lagi. Seperti biasanya, dia membawakan saya sebatang cokelat (dia mungkin lupa saya sudah berusia empat puluh delapan tahun); seperti biasanya, kami berbincang dan menertawakan tentang kehidupan, politik, dan gosip keluarga. Datang masanya ketika sepasang mata ayah saya memandang ke sudut di mana dia dulu menaruh kopernya dan menyaksikan bahwa saya telah memindahkannya. Kami saling bersitatap satu sama lain. Kemudian diikuti oleh kesunyian yang menekan. Saya tak memberitahunya bahwa saya telah membuka koper itu dan berusaha membaca isinya; alih-alih, saya memalingkan pandang ke kejauhan. Namun dia mengerti. Persis seperti saya mengerti bahwa dia mengerti. Persis seperti dia mengerti bahwa saya mengerti bahwa dia mengerti. Namun semua pengertian ini hanya berlangsung beberapa saat saja. Lantaran ayah saya seorang yang bahagia, lelaki periang yang percaya kepada dirinya sendiri: dia tersenyum kepada saya dengan senyum yang seperti biasanya. Dan ketika dia meninggalkan rumah, dia mengulang mengucapkan sesuatu yang menyenangkan dan menyemangati yang selalu dia katakan kepada saya, galibnya seorang ayah.
Seperti biasanya, saya mengawasi kepergiannya, sembari cemburu pada kebahagiaannya, temperamennya yang lepas-bebas dan tak terusik. Tapi saya ingat bahwa pada hari itu juga ada seberkas kegembiraan dalam diri saya yang membuat saya merasa malu. Hal itu didorong oleh pikiran bahwa mungkin saya tak merasa nyaman dalam kehidupan sebagaimana ayah saya, mungkin saya tak menjalani kehidupan sebahagia dan selepas kehidupan dia, tapi itu karena saya mempersembahkan hidup saya untuk menulis — Anda tentu sudah mengerti… saya merasa malu memikirkan segala tentang jasa ayah saya. Dari semua orang, ayah sayalah, yang telah membiarkan saya bebas. Semua ini seharusnya mengingatkan kita bahwa tulisan dan sastra secara akrab terpaut pada kekurangan akan pusat dalam kehidupan kita, dan pada perasaan bahagia dan rasa bersalah kita.
Namun cerita saya memiliki simetri yang segera mengingatkan saya tentang sesuatu yang lain pada hari itu, dan yang membuat saya bahkan merasa lebih bersalah lagi. Dua puluh tiga tahun sebelum ayah saya memberikan kopernya, dan empat tahun setelah saya memutuskan, pada usia dua puluh dua tahun, untuk menjadi novelis, dan meninggalkan segalanya, untuk mengurung diri di sebuah kamar, saya merampungkan novel pertama saya, bertajuk Cevdet Bey and Sons; dengan tangan gemetar saya menyerahkan draf novel saya yang belum diterbitkan kepada ayah saya agar dia bisa membacanya dan memberi pendapat tentangnya. Ini bukan hanya lantaran saya percaya terhadap selera dan inteleknya: pendapat ayah saya sangat penting bagi saya karena dia, tak seperti ibu saya, tak menentang saya untuk menjadi penulis. Pada titik itu, ayah saya tidak bersama kami, melainkan berada di tempat jauh. Saya menanti-nanti dengan sabar kepulangannya. Saat dia datang dua minggu kemudian, saya berlari untuk membuka pintu. Ayah saya tak berucap sepatah kata pun, namun dia merangkulkan lengannya kepada tubuh saya, suatu cara untuk mengatakan kepada saya bahwa dia sangat menyukainya. Untuk sejenak, kami terisap dalam semacam kesunyian yang canggung, yang kerap kali hadir menemani momen-momen tertentu dengan emosi yang mengharukan. Lantas, saat kami sudah tenang kembali dan mulai berbincang, ayah saya mengutarakan dalam bahasa yang berlebihan demi mengekspresikan kepercayaannya kepada saya atau novel pertama saya: dia bilang kepada saya bahwa pada suatu hari, saya akan memenangkan penghargaan yang saat ini telah saya terima dengan kebahagiaan tiada tara.
Ayah saya mengatakan hal ini bukan karena dia berusaha meyakinkan saya tentang pendapat baiknya, atau untuk menjadikan penghargaan ini sebagai tujuan; dia mengatakan hal ini seperti seorang ayah dari Turki yang memberikan dukungan kepada anaknya, menyemangatinya dengan mengatakan, “Suatu hari kau akan menjadi pasha[1]!” Selama bertahun-tahun, kapan pun dia melihat saya, dia akan menyemangati saya dengan kata-kata yang sama.
Ayah saya wafat pada Desember 2002.
Kini, saat saya berdiri di hadapan Akademi Swedia dan para juri terhormat yang telah menganugerahi saya penghargaan besar ini — kehormatan besar ini — serta para tamu terhormat, saya sungguh berharap beliau berada di antara kita. ♦
[1] Orang terhormat.—ed.
Tambahan info : Terjemahan ini terbit pertama kali pada Majalah Sastra Horison, edisi Desember 2014. Bacaan ini khusus bagi yang membaca teks panjang dengan sabar, dan tidak suka grusa-grusu. Saya tahu. pembaca FB pada umumnya lebih suka bacaan yg pendek, dan instant. Selama ini, saya akjui hanya membagikan penggalan2nya saja sebagai status. Tapi kali ini tidak. Saya sungguh2 menyarankan Anda membacanya sampai tamat. :-) (Muhammad Asqalani )
Opini saya:
Ada sebuah celetukan beredar di media sosial, "Jikalau kita bisa menahan diri untuk tidak membuka media sosial, namun tetap melanjutkan kegiatan menulis dan membaca, kemungkinan bisa sampai dua ratus buku habis dalam setahun." Saya kira, memang pada dasarnya manusia telah memiliki naluri untuk menulis, entah memiliki akun media sosial atau tidak. Kumpulan perasaan Orhan Pamuk yang cukup menguji kesabaran untuk meresapi setiap kalimatnya mengindikasikan bahwa naluri menulis itu memang sejalan dengan dinamika dalam pikiran yang berkecamuk.
Segala sesuatu yang rumit, seringkali berawal dari hal yang sederhana. Tekad raksasa Orhan untuk menyelami dunia literasi kiranya bersinggungan dengan suatu benda yang melekat dalam ingatannya sejak dini. Koper sang ayah. Jikalau bercermin dengan diri kita ini, rasanya ada banyak anasir-anasir sederhana yang menguatkan hasrat untuk menghubungkan perasaan dengan kejadian-kejadian yang ada di dunia. Teruntuk saya sendiri, minat untuk menyelami non-fiksi berasal dari kunjungan ke museum dinosaurus di London. Teruntuk para pembaca, setiap fragmen yang memunculkan hasrat itu merupakan cetak biru bagaimana cita-cita literasi dipahat dengan seksama.
Sederhananya, cita-cita yang sedang kita perjuangkan saat ini untuk menggelorakan semangat literasi, tak lepas dari kenangan-kenangan yang menembus batin. Entah lapisan hati yang ke berapa, barangkali cukup dalam hingga bertahta dalam ingatan. Maka darinya, kalaupun beberapa tahun, atau mungkin sekian minggu ke depan, nafsu menulis itu lenyap: hendaknya kita jadikan menulis itu sebagai satu-satunya sarana untuk memahat sejarah. Terlepas dari sejarah seperti apa yang tercetak, terlalu sayang bila ingatan-ingatan hanya menguap lenyap bersama cuaca udara yang terus berubah.
Dalam curahan hati Orhan ini, takkan bisa kita sangkal bahwa fiksi-non-fiksi yang menjadi santapan mata lalu ke pikiran adalah suatu bentuk pelarian bahkan perlawanan terhadap realita. Dengan demikian, hendaknya suatu inisiasi pikiran ini berpotensi untuk dikonversi menjadi semangat mencari kebenaran, pengetahuan, dan pencerahan yang utuh. Memang patut diakui membaca bukanlah kegiatan yang selalu mengandung rekreasi. Sesekali dimensi otak harus terlatih mencerna diksi dan makna, untuk bisa mengabadikannya hingga ke dalam hati. Pertanyaan besarnya: sampai hari ini, buku bacaan seperti apa sajakah yang telah membentuk dunia kita? Saya tak ragu menyebut kumpulan humor madura yang tak lebih dari seratus sepuluh halaman itu memainkan peranan besar dalam menjerumuskan diri ini untuk mencintai buku tanpa gambar. Kalaulah saya boleh banyak berdoa, semoga Pak Haji Musa mendapat banyak pahala karena menghadirkan hiburan segar ditambah muatan budaya lokal dikala badan mendekam di rumah sakit dengan posisi tangan terhubung infus.
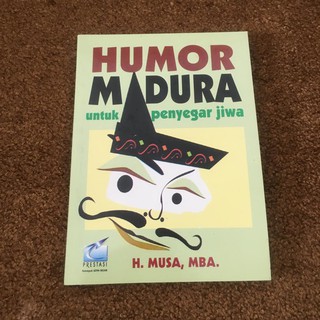
Opini saya:
Ada sebuah celetukan beredar di media sosial, "Jikalau kita bisa menahan diri untuk tidak membuka media sosial, namun tetap melanjutkan kegiatan menulis dan membaca, kemungkinan bisa sampai dua ratus buku habis dalam setahun." Saya kira, memang pada dasarnya manusia telah memiliki naluri untuk menulis, entah memiliki akun media sosial atau tidak. Kumpulan perasaan Orhan Pamuk yang cukup menguji kesabaran untuk meresapi setiap kalimatnya mengindikasikan bahwa naluri menulis itu memang sejalan dengan dinamika dalam pikiran yang berkecamuk.
Segala sesuatu yang rumit, seringkali berawal dari hal yang sederhana. Tekad raksasa Orhan untuk menyelami dunia literasi kiranya bersinggungan dengan suatu benda yang melekat dalam ingatannya sejak dini. Koper sang ayah. Jikalau bercermin dengan diri kita ini, rasanya ada banyak anasir-anasir sederhana yang menguatkan hasrat untuk menghubungkan perasaan dengan kejadian-kejadian yang ada di dunia. Teruntuk saya sendiri, minat untuk menyelami non-fiksi berasal dari kunjungan ke museum dinosaurus di London. Teruntuk para pembaca, setiap fragmen yang memunculkan hasrat itu merupakan cetak biru bagaimana cita-cita literasi dipahat dengan seksama.
Sederhananya, cita-cita yang sedang kita perjuangkan saat ini untuk menggelorakan semangat literasi, tak lepas dari kenangan-kenangan yang menembus batin. Entah lapisan hati yang ke berapa, barangkali cukup dalam hingga bertahta dalam ingatan. Maka darinya, kalaupun beberapa tahun, atau mungkin sekian minggu ke depan, nafsu menulis itu lenyap: hendaknya kita jadikan menulis itu sebagai satu-satunya sarana untuk memahat sejarah. Terlepas dari sejarah seperti apa yang tercetak, terlalu sayang bila ingatan-ingatan hanya menguap lenyap bersama cuaca udara yang terus berubah.
Dalam curahan hati Orhan ini, takkan bisa kita sangkal bahwa fiksi-non-fiksi yang menjadi santapan mata lalu ke pikiran adalah suatu bentuk pelarian bahkan perlawanan terhadap realita. Dengan demikian, hendaknya suatu inisiasi pikiran ini berpotensi untuk dikonversi menjadi semangat mencari kebenaran, pengetahuan, dan pencerahan yang utuh. Memang patut diakui membaca bukanlah kegiatan yang selalu mengandung rekreasi. Sesekali dimensi otak harus terlatih mencerna diksi dan makna, untuk bisa mengabadikannya hingga ke dalam hati. Pertanyaan besarnya: sampai hari ini, buku bacaan seperti apa sajakah yang telah membentuk dunia kita? Saya tak ragu menyebut kumpulan humor madura yang tak lebih dari seratus sepuluh halaman itu memainkan peranan besar dalam menjerumuskan diri ini untuk mencintai buku tanpa gambar. Kalaulah saya boleh banyak berdoa, semoga Pak Haji Musa mendapat banyak pahala karena menghadirkan hiburan segar ditambah muatan budaya lokal dikala badan mendekam di rumah sakit dengan posisi tangan terhubung infus.
Hiburan 'mulia' dikala opname sulit menghindari.
Baru-baru ini, sebuah istilah Jepang mulai mengudara untuk menyebut secara spesifik para penumpuk buku. Shundoku. Diartikan sebagai orang-orang yang gemar membeli buku, menyimpannya, tapi lupa membacanya. Ada kalanya, dalam perjalanan meningkatkan daya literasi, kita cenderung latah mengira bahwa tingkat ketajaman membaca berbanding lurus dengan jumlah kepemilikan buku. Padahal, penulis dunia sekaliber Jorge Luis Borges saja hanya melahap dan mengingat tujuh puluh enam buku. Tujuh puluh enam, semenjak membaca menjadi rutinitasnya hingga ke liang lahat. Bagaimanakah dengan kita yang masih tumpul dalam memilah bacaan?
Dua puluh empat jam adalah harga mati jumlah waktu yang kita punya dalam sehari. Di antara tumpukan buku-buku yang sempat latah diborong, mungkin saja yang bisa diingat hanya bisa dihitung jari. Di lain sisi, perasaan latah untuk memborong buku ini adalah hal wajar. Orhan Pamuk telah menggemakannya dalam perasaan bahwa menjadi penulis akan sulit untuk menghindari kegalauan. Kegalauan akut mengenai dunia alternatif yang lebih baik, hingga pertanyaan tak henti tentang tujuan dari segala realita dunia yang sedang dihadapi. Di titik itu, Orhan Pamuk saya tafsirkan sedang bermonolog:
"Apakah segala kerumitan hidup yang sedang saya jalani mengarah pada suatu skenario?"
Bukan tidak mungkin, ketika karya-karya kumpulan perasaan dan pemikiran kita telah terbungkus hangat dan dibaca orang yang tepat, di sanalah takdir baru tercipta. Kiranya ini yang dihadapi oleh relung hati Orhan saat menyerahkan karya untuk dibaca sang Ayah. Sesekali, tidak ada salahnya bila karya kita persembahkan terlebih dahulu untuk orang terdekat. Seperti halnya genangan muncul setelah hujan, timbul kenangan setelah menjadi perasaan, lalu menjadi sejarah berkelanjutan setelah menjadi tulisan.
Dengan meninjau pidato Orhan Pmauk, saya ingin berbagi harapan. Sederhana tetapi mungkin butuh perjuangan, bahwa tulisan yang kita hasilkan menjadi kapsul waktu yang merangkum segenap perasaan dan pemikiran, lalu tercetak menjadi kisah turun-temurun yang membahana dalam setiap ruang diskusi. Tak lupa, jangan lupa untuk kembali 'membaca' apa yang menjadi pilihan dalam membaca. Sebagaimana hidung memilah zat kimia untuk bernafas, hendaknya mata dipergunakan untuk memilah dan mengabdikan hal-hal yang bermanfaat sebagai penenun ingatan yang kelak menjadi sejarah pertumbuhan diri.
Dengan hormat,
Briantono.


He he aku senang membaca baru novel ringan sebagai hiburan 🤩🤩
BalasHapusoh novel ringan, pasti memang enak untuk sajian otak.
BalasHapusShundoku. Mudah-mudahan ngga jadi seperti itu hiks. Bahkan tumpukan buku itu nantinya akan ditanya di akhirat, udah seberapa besar manfaat dari keberadaannya?
BalasHapusBTW yg sakit semoga cepat sembuh. Aamiin